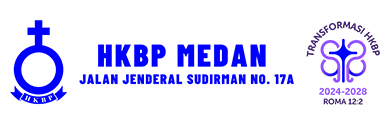Tema dan Sub Tema Rapat Pendeta HKBP 2025:
TEMA: “CIPTAAN BARU“(2 KORINTUS 5:17)
Sub Tema: “Pendeta HKBP Diutus Mengemban Pastoral Profetik dan Menghadirkan Transformasi Gereja dan Masyarakat yang Terbebas dari Belenggu Korupsi, Perjudian, Narkoba, Perdagangan Manusia dan Kerusakan Alam“.
Konteks dan Latarbelakang; Rekonsiliasi Sentral Utama
Surat 2 Korintus ini ditulis dalam situasi pasca-konflik antara Paulus dan jemaat di Korintus, yang mempertanyakan otoritas kerasulannya. Itu sebabnya surat ini acap disebut sebagai surat air mata (2 Kor 2:4).
Dalam membela pelayanannya, Paulus tidak hanya mengemukakan legitimasi kerasulannya, tetapi menyingkapkan kedalaman spiritualitasnya yang dibentuk oleh salib dan kebangkitan.[1] Kasih Kristus adalah kekuatan pendorong misi kerasulannya (ay. 14). Konsekuensi logisnya, yang hidup dalam Kristus tidak lagi hidup untuk diri sendiri (ay. 15).
Kebangkitan Yesus membingkai iman untuk memahami bahwa siapa pun yang ada di dalam Kristus sudah termasuk dalam tatanan kebaharuan eskatologi yang terwujud. Kebangkitan Yesus telah mengawali penciptaan baru (lih. 2 Kor. 4:6), sebagai hasil rekonsiliasi dari kematian Kristus (2 Kor. 5:14-15; Rm. 5:10).
Rekonsiliasi (καταλλαγή – katallage: 5 kali ay 18-20). Berarti rekonsiliasi bukan bagian kecil dari pemberitaan Firman, melainkan inti dari karya Allah. Rekonsiliasi membuat musuh jadi teman (Rm 5:10; Ef 2:14-16). Rekonsiliasi mencakup menerima teman- teman sahabat sebagai teman sendiri. Bagaimana mungkin orang Korintus berdamai dengan Allah namun tidak memercayai utusanNya (bnd. Mat. 10:40)?[2]
Paulus mengajak jemaat Korintus untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Dia datang ke tempat di mana semua penyembuhan sejati ditemukan, yaitu dalam Yesus yang tersalib. Itulah yang memungkinkan Paulus berbicara tentang hubungan yang dipulihkan. Rekonsiliasi bukan saja tentang relasi personal membarui hubungan manusia dengan Allah, tetapi membentuk komunitas baru sebagai “..utusan-utusan Kristus..” (ay 20).
Berarti setiap “ciptaan baru” ditransformasi menjadi agen rekonsiliasi guna memulihkan seluruh tatanan ciptaan.[3] Paulus menegaskan bahwa pendamaian dalam Kristus tidak hanya bersifat vertikal (antara manusia dan Allah), tetapi juga horizontal (antara manusia dengan sesama dan dengan ciptaan).
“Ada di dalam Kristus” (ἐν Χριστῷ – en Kristo)
“Ada di dalam Kristus” (ἐν Χριστῷ – en Kristo): ἐν – en, sebuah preposisi dengan arti: di dalam, menyatu dengan. Χριστῷ – Kristo: Mesias, yang diurapi. Berarti: ἐν Χριστῷ – en Kristo menyatakan sebuah identitas baru dalam komunitas yang diurapi.
Frasa ini bukan berarti sekadar menjadi “member” dalam komunitas religius, melainkan sebuah realitas ontologis dan eksistensial, yang mengalami penyatuan dengan kematian dan kebangkitanNya.[4] Ini melampaui transformasi moral, menyentuh seluruh eksistensi manusia, termasuk orientasi sosial dan relasi kosmis. “Ada dalam Kristus” ekuivalen dengan: menjadi ciptaan baru; milik Kristus; hidup dalam kuasa Kristus; bersatu dengan Kristus, satu dalam komunitas Kristen.
“Ciptaan baru” (καινὴ κτίσις – kaine ktisis)
Kata Yunani καινὴ-kaine berarti baru dalam kualitas; bukan baru secara kronologis. Κτίσις – ktisis dari kata kerja Κτίzo-ktizo berarti: Mencipta (sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya).
Frasa ini bukan soal perbaikan moral individual, melainkan partisipasi dalam realitas baru yang telah dan sedang diaktualkan dalam Kristus. Kαινὴ – kaine, bukan “baru” dalam arti temporal (neos- neos), tetapi “baru” dalam kualitas dan esensi.[5] Ini menandai keterlibatan orang percaya dalam realitas Kerajaan Allah di dunia.
Ciptaan baru menekankan “transformasi radikal” yang terjadi ketika seseorang diperdamaikan dengan Allah. Ciptaan baru diutus menjadi tubuh Kristus yang memperdamaikan dalam relasi sosial, politik, ekologis, dan spiritual.
“Yang lama sudah berlalu, yang Baru sudah datang”
Kata arcaia – arkhaia dengan akar kata arch – arkhe berarti: awal, sumber, permulaan, menghunjuk kepada hal-hal yang lama sebelum Kristus, yakni dosa dan identitas duniawi. Kata: parelqhn – aparelthen (aoris tense aktif dari parercomai – parerkhomai) berarti melewati, lenyap dan berakhir, tindakan tuntas di masa lalu.
Ungkapan ini menyiratkan kematian terhadap struktur dan sistem dunia lama yang dikendalikan oleh dosa, kekuasaan yang korup, relasi yang eksploitatif dan spiritualitas yang memisahkan iman dari praksis.[6] Lewat kematian Kristus, sistem lama tersebut telah dihapuskan (Kol. 2:14–15), maka orang percaya dipanggil untuk memutus keterikatan terhadap struktur itu.[7]
“Telah Menjadi”
Kata γέγονεν – gegonen perfect tense dari gignomai -gignomai artinya: telah menjadi, tercipta. Perfect tense dari gignomai- gignomai menghunjuk kepada hasil yang sudah berlangsung dari tindakan di masa lalu, sehingga muncul realitas yang baru yang terus memberi dampak hingga sekarang dan nanti.
Struktur Yunani γέγονεν – gegonen menekankan bahwa realitas baru telah hadir dan sedang berlangsung. Hidup dalam Kristus merupakan aktualisasi dari eksistensi eskatologis pada masa kini.[8] Hal ini menyiratkan bahwa transformasi pribadi membawa serta tanggung jawab sosial.
Dimensi Etis dan Sosial dari “Ciptaan Baru”
Ciptaan baru tidak pernah berdiam dalam ranah privat. Paulus sendiri, setelah mengalami transformasi eksistensial dalam Kristus, dia menjadi agen pendamaian dalam konteks sosial yang rusak. Ciptaan baru dipahami dalam kaitannya dengan transformasi struktural dan keberpihakan kepada keadilan.[9] Konsekuensinya, setiap pemimpin gereja, tidak dapat menghindar dari tanggung jawab kenabian untuk menghadirkan praksis Kerajaan Allah dalam sejarah.
Institusi Gereja: “Ciptaan Baru” dan Komunitas Profetik
Gereja harus bertransformasi. Transformasi personal para pendeta harus berdampak pada institusi gereja. Gereja sebagai “ciptaan baru” tidak boleh terjebak dalam birokratisasi pelayanan, tetapi harus menjadi komunitas yang hidup, dinamis dan relevan, yang menuntut pembaruan cara berpikir (Rom 12:2) dan struktur pelayanan yang mendukung keterlibatan umat dalam misi profetik.
HKBP memerlukan eklesiologi yang sifatnya tidak hanya administratif, tetapi spiritual dan misiologis. Kepemimpinan tidak patut dibangun atas dasar senioritas atau kelaziman birokratis, melainkan karakter, kapasitas analisis sosial-teologis dan integritas moral. Pelatihan pendeta dibaharui dengan kurikulum teologi publik, spiritualitas kontekstual, dan advokasi sosial.
Gereja sebagai komunitas ciptaan baru terpanggil menjadi pelopor keadilan dan damai sejahtera. Gereja bukan sekedar tempat ibadah, tetapi pusat transformasi, ruang rekonsiliasi lintas masyarakat, tempat perlindungan korban kekerasan dan pelaku aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Gereja profetik bukanlah gereja yang populer, tetapi gereja yang setia memberitakan firman pada seluruh ciptaan.
Pastoral Profetik: Konsep dan Relevansi
Pastoral profetik bukan saja perawatan jiwa, tetapi keberpihakan pada konteks hidup umat. Dimensi kontemplasi diintegrasikan dengan aksi transformatif, dengan meneladani para nabi Perjanjian Lama dan hidup Yesus yang menggabungkan spiritualitas dengan kritik sosial yang tajam. Pastoral profetik menjadi fungsi institusional dan panggilan untuk menjadi suara Allah dalam konteks yang konkret.
Dalam struktur HKBP yang memiliki pengaruh sosial dan budaya yang luas, para pendeta memainkan peran strategis dalam membentuk kesadaran umat. Identitas sebagai ciptaan baru harus diwujudkan dalam kepemimpinan profetik yang mampu membongkar dosa struktural, membela kaum marginal dan menginisiasi praksis pembebasan. Hal ini membutuhkan formasi spiritual yang mendalam, analitis yang tajam akan realitas sosial, dan keberanian menanggung risiko dalam menyuarakan kebenaran.
Pendeta HKBP dengan Identitas “Ciptaan Baru”
Transformasi identitas dalam Kristus tidak saja menyentuh wilayah spiritual privat. Pendeta sebagai ciptaan baru menjadi “inkarnasi” dari nilai-nilai Kerajaan Allah: keadilan sosial, belas kasih, keberanian moral, dan integritas. Dalam konteks HKBP yang sinodal dan hierarkis, otentisitas spiritual ini menjadi kekuatan moral guna membangun ekosistem gerejawi yang sehat dan transformatif.
Pendeta bukan hanya pembaru liturgi atau pengajar dogma, tetapi pelaku aktif dalam transformasi sosial dan ekologis. Ia membentuk habitus profetik dalam komunitas, mengadvokasi kebijakan publik yang adil, dan membangun solidaritas dengan kelompok tertindas. Identitas baru menjadi kekuatan transformatif guna menjangkau seluruh dimensi hidup manusia dan ciptaan.
Misi Transformasi: Menjawab Kejahatan Struktural
Indonesia, termasuk masyarakat Batak sebagai basis pelayanan HKBP, sedang menghadapi pergumulan multi-dimensi yang serius. Korupsi merusak struktur pemerintahan dan kepercayaan publik; judi dan narkoba menghancurkan generasi muda; praktik perdagangan manusia menistakan martabat ciptaan Allah; kerusakan dan eksploitasi ekologis mencerminkan krisis spiritual dan etis yang akut.
Dalam konteks ini, gereja dipanggil menghidupi peran profetiknya, dengan para pendeta sebagai ujung tombak transformasi spiritual, sosial, dan ekologis, sambil membaharui individu maupun artikulasi teologis yang soteriologis.
Transformasi yang dikerjakan oleh pendeta sebagai ciptaan baru tidak berada dalam ruang hampa, melainkan bergumul langsung dengan berbagai struktur dosa yang merusak tatanan sosial, moral, dan ekologis masyarakat. Pendeta tidak hanya diutus untuk berkhotbah dan menggembalakan, melainkan menjadi saksi Kristus yang menubuatkan kehendak Allah terhadap dunia yang rusak.
Inilah 5 ranah kejahatan struktural yang menuntut intervensi kenabian gereja:[10]
Korupsi: Pembusukan Moral dan Tantangan Etika Gerejawi
Korupsi adalah pelanggaran hukum dan ekspresi nyata dari antitesis terhadap keadilan Allah. Dalam Alkitab, ketidakadilan struktural kerap menjadi sasaran kecaman para nabi (Yes. 1:23; Mik. 3:11). Di Indonesia, korupsi menjadi sistemik, merusak kepercayaan publik, dan menyandera kebijakan yang seharusnya menyejahterakan rakyat. Pendeta HKBP sebagai ciptaan baru memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan etos transparansi dan integritas, baik dalam struktur gereja maupun masyarakat.
Harian KOMPAS fenomena ini sebagai “Liga Korupsi Indonesia”. Per Juni 2025 beberapa kasus korupsi mencuat ke publik, seperti: Korupsi Pertamina sekitar 968 triliun, kasus PT Timah sekitar 300 triliun, kasus BLBI sekitar 138 triliun, Korupsi PT Asabri 22 triliun lebih, Kasus PT Jiwasraya 16 triliun lebih, Kasus korupsi Wilmar atau CPO sekitar 11 triiun lebih dan lain-lain.
Kejahatan korupsi yang sangat luar biasa ini sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak kepercayaan investor, memperdalam kesenjangan sosial, dan lain-lain. Situasi ini, selain menuntut tindakan hukum yang tegas, juga menekankan pentingnya transformasi budaya politik, etika kepemimpinan. Perang melawan korupsi sering menjadi politik pencitraan ketimbang memberantas kejahatan yang sistemik dan massif ini. Pemerintah bersama kita harus mendudukkan orang-orang yang tidak rakus mengejar harta dan kuasa dalam segenap birokrasi yang vital. Gereja mengutuk kejahatan luar biasa ini. Gereja mesti kritis, jangan sampai donasi untuk kegiatan agama berasal dari donateur kaya yang licik mengakali pembayaran pajak, bahkan berasal dari hasil memeras masyarakat dari hasil korupsinya, yang sungguh bertentangan dengan taurat ke-8.
Hal ini dapat dimulai dengan menempa dan membiasakan diri menjadi teladan publik yang akuntabel dalam mengelola keuangan jemaat. Lalu, mendampingi komunitas guna membangun kesadaran kritis terhadap praktik korupsi. Pendidikan etika sosial berbasis iman menjadi alat penting guna membentuk umat agar imun terhadap korupsi.
Perjudian: Eksploitasi Ekonomi dan Krisis Spiritual
Perjudian menggerus nilai kerja keras dan memperbudak umat dengan ilusi keberuntungan. Pendeta terpanggil membongkar akar ketergantungan pada perjudian, yakni keputusasaan eksistensial dan alienasi dari komunitas sehat.
Tugas pastoral profetik: membangun spiritualitas dan ketekunan, serta menghadirkan gereja sebagai ruang pemulihan identitas dan martabat. Liturgi, pengajaran, dan konseling harus diarahkan untuk membebaskan umat dari struktur adiktif ini, sambil menyuarakan kritik moral terhadap sistem ekonomi yang melegitimasi praktik spekulatif dan destruktif ini.
Presiden Republik Indonesia mencanangkan program Asta Cita ke-7 menyangkut judi dan narkoba, dengan memberi perhatian kepada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba dan penyelundupan. Judi daring di Indonesia menunjukkan trend kenaikan yang signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023, bahwa total transaksi perjudian online mencapai 327 triliun, dengan pelaku sekitar 2,37 juta orang terlibat di dalamnya, dengan 80 persen di antaranya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Bahkan tercatat sekitar 960.000 orang pelajar dan mahasiswa teridentifikasi sebagai pengguna aktif platform judi online ini.
Masih dalam laporan PPATK, bahwa selama kuartal pertama tahun 2025 (Januari-Maret), tercatat sejumlah 1.066.000 pemain judi online di Indonesia. Sebanyak 71 persen dari pemain tersebut berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Hal ini tentu sangat beresiko terhadap kebutuhan hidup mereka. Dari segi usia, mayoritas pemain judi online ini adalah kelompok usia produktif antara 20-30 tahun (sebanyak 396 ribu orang) dan usia 31-40 tahun sebanyak 395 ribu orang. Judi online adiktif ini ternyata terus menyasar kelompok rentan secara ekonomi maupun usia.
Narkoba: Disorientasi Antropologis dan Tanggung Jawab Pemulihan
Kecanduan narkoba merepresentasikan krisis eksistensial dan spiritual yang mendalam. Di berbagai wilayah pelayanan HKBP, narkoba menjerat generasi muda dan menghancurkan potensi kemanusiaan. Sebagai ciptaan baru, pendeta tidak dapat bersikap netral atau menyerah pada stigma sosial ini.
Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan kasus narkoba tahun 2024 mencapai 9.348 kasus dengan tersangka berjumlah 12.137 orang. Khusus di Sumatera Utara ada 691 kasus dan 858 orang ditahan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah persebaran Narkotika tertinggi, dengan perputaran uang mencapai 99 triliun (www. Indonesia darurat narkoba…). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta jiwa, dengan mayoritas pengguna dari kalangan generasi muda. Indonesia tidak lagi hanya sekedar menjadi sasaran pasar distribusi narkoba, tetapi juga mulai berperan sebagai produsen. Penanggulangan krisis ini membutuhkan pendekatan lintas sektor, terpadu dan berkelanjutan guna memutus rantai produksi, distribusi serta penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
Pendeta menjadi pelayan pemulihan, memfasilitasi rehabilitasi pastoral, mendampingi keluarga yang terdampak, gereja tempat penerimaan dan bukan penghakiman. Juga bersuara terhadap jaringan kriminal dan aparat yang bermain dalam distribusi narkoba, seperti sikap profetik Yesus melawan struktur kuasa yang menindas.
Perdagangan Manusia: Krisis Martabat dan Aksi Profetik Gereja
Perdagangan manusia adalah perbudakan modern yang merusak imago Dei. Gereja sebagai komunitas ciptaan baru, tidak dapat diam terhadap praktik ini, baik dalam bentuk migrasi paksa, eksploitasi seksual maupun tenaga kerja. Pendeta HKBP terpanggil menjadi gembala yang menelusuri domba yang hilang, sekaligus nabi yang mengutuk sistem yang memperdagangkan tubuh dan jiwa manusia.
Perdagangan manusia (“human trafficking”) merupakan bentuk modern dari perbudakan dan pelanggaran serius akan hak azasi manusia, dengan modus operandi pemaksaan, penipuan dan eksploitasi. Korban perdagangan manusia ini acap berasal dari berbagai kelompok rentan, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki dan perempuan. Latarbelakangnya dan motivasinya kerap karena kemiskinan atau tekanan ekonomi dan pengangguran, agen tenaga kerja illegal karena untung yang tinggi, janji palsu, terlilit hutang dan pemerasan.
Perdagangan manusia ini sesungguhnya bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut teologi, karena semuanya itu merusak diri manusia sebagai Imago Dei. Segenap bentuk kejahatan yang merendahkan bahkan meniadakan martabat manusia merupakan dosa sosial yang mencederai rupa Allah sebagai Imago Dei. Segala bentuk eksploitasi manusia sebagai alat ekonomi sesungguhnya adalah kekejian bagi Tuhan dan sesama manusia (Pengakuan Iman HKBP 1996 pasal 3 tentang manusia). Manusia sesungguhnya adalah mitra kerja Allah di dalam Kerajaan Allah.
Gereja dapat membentuk jaringan advokasi, bekerja sama dengan LSM dan pemerintah untuk pencegahan, perlindungan korban serta rehabilitasi. Pendidikan teologis sejatinya memasukkan isu human trafficking sebagai materi pembentukan kepekaan kenabian dalam formasi calon pelayan.
Kerusakan Alam: Krisis Ekologis dan Spiritualitas Ciptaan
Krisis ekologis mencerminkan relasi yang rusak antara manusia dan ciptaan, sebagai akibat dari konsep teologi yang memisahkan keselamatan dari bumi. Dalam Kristus, seluruh ciptaan didamaikan (Kol. 1:20), dan gereja dipanggil untuk mengambil bagian dalam rekonsiliasi kosmis ini.
Tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah pemanasan global dengan dampak yang sangat luas. Pemanasan global ini menyebabkan kenaikan permukaan laut, bencana alam, badai, kekeringan, gelombang panas, kebakaran hutan dan bencana lainnya. Tantangan ekologis ini menempatkan alam sebagai objek eksploitasi, bukan saja sebagai krisis sekuler atau profan, melainkan juga sebagai krisis spiritual. Segala sesuatu diciptakan Allah, oleh Dia dan untuk Dia (Kolosse 1:15-20). Karya penyelamatan Kristus sejatinya meliputi seluruh ciptaan.
Dalam Pengakuan Iman HKBP 1996 pasal 5 tentang Kebudayaan dan Lingkungan hidup menyebutkan bahwa Allah menciptakana manusia dengan tempat tinggalnya dan tempat bekerja di dunia ini (Kej 2:5-15). Manusia terpanggil untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia dapat bekerja, sehat dan sejahtera (Mzm 8:4-10). HKBP menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, maupun setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga marusak air minum dan pernafasan manusia. Hal ini juga bertentangan dengan titah ke-6 yang melawan pembunuhan.
Pendeta mengembangkan spiritualitas ekologis dalam pelayanan: liturgi yang menghormati bumi, khotbah yang membongkar dosa ekologis, aksi kolektif menjaga lingkungan hidup. HKBP, dengan tanah adat dan hutan yang menjadi bagian dari konteksnya, memiliki peluang besar menjadi pionir teologi ekologi kontekstual.
Kesimpulan
Identitas dalam Kristus memampukan seseorang hidup sebagai ciptaan baru, sebagai partisipan dalam realitas Kerajaan Allah. Pendeta HKBP terpanggil menjadi subjek transformasi spiritual, agen pembaruan sosial, dan pelayan rekonsiliasi kosmis. Dalam dunia yang dilanda korupsi, ketergantungan, dan eksploitasi alam, pendeta tidak boleh menjadi administrator liturgi belaka, tetapi nabi yang menyuarakan kehendak Allah guna menyatakan gereja yang transformatif.
Pendeta HKBP terpanggil benar-benar hidup dalam identitas baru guna memperjuangkan nilai-nilai Kerajaan Allah secara konkret. Pendeta dan pelayan secara umum, bagian ini bukan hanya dasar spiritualitas pribadi, tetapi juga fondasi teologis untuk pelayanan pastoral profetik, yang menghibur, memperdamaikan, membongkar dosa struktural, dan mengupayakan keadilan Allah di dunia.
Seruan profetik kepada gereja dan para pelayan: berubahlah dalam Kristus, dan ubahlah dunia bersamaNya. Identitas sebagai ciptaan baru bukanlah status statis, melainkan proses berkelanjutan dalam misi Allah yang membebaskan, menyembuhkan, dan memperbarui segala sesuatu—hingga bumi dan langit yang baru dinyatakan sepenuhnya (Why. 21:1–5).
Selamat mengikuti Rapat Pendeta HKBP, 27-30 Oktober 2025 untuk segenap teman-teman para pendeta HKBP dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Tuhan memberkati HKBP dan memberkati kita semua serta memberkati segenap pelayanan kita. Amin !
[1] Colin G. Kruse, “2 Korintus,” in Tafsiran Alkitab Abad Ke-21 – Matius-Wahyu (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2017), 415–418; Stephen M. Miller, Panduan Lengkap Alkitab (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 455–457.
[2] Keener, 1-2 Corinthians – The New Cambridge Bible Commentary, 185–186.
[3] Joas Adiprasetya, Berteologi Dalam Iman: Dasar-Dasar Teologi Sistematika-Konstruktif (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 154–156.
[4] Mitzi L. Minor, 2 Corinthians – Smyth & Helwys Bible Commentary (Macon: Smyth & Helwys Publishing, 2009), 112.
[5] Hughes, The Second Epistle to the Corinthians – The New International Commentary on the New Testament, 203.
[6] Jan Lambrecht, Second Corinthians – Sacra Pagina, ed. Daniel J. Harrington (Collegeville: The Liturgical Press, 1998), 97.
[7] Frank J. Matera, II Corinthians: A Commentary – The New Testament Library (Louisville: Westminster John Knox Press, 2013), 136.
[8] Lambrecht, Second Corinthians – Sacra Pagina, 97.
[9] Minor, 2 Corinthians – Smyth & Helwys Bible Commentary, 113.
[10] Sebagai refleksi atas Stott, The Living Church: Menanggapi Pesan Kitab Suci Yang Bersifat Tetap Dalam Budaya Yang Berubah, 33–59.